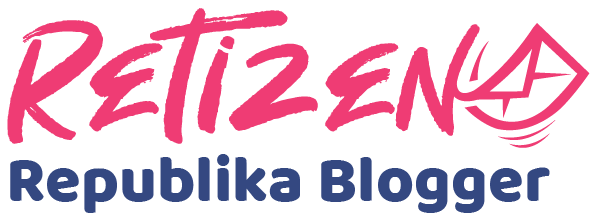Analisis Wacana Media 2025: Tren, Tantangan dan Implikasinya bagi Publik

REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Di era digital 2025, wacana media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, agenda politik, dan kebijakan sosial.
Menurut laporan Reuters Institute Digital News Report 2024-2025, pengguna berita daring di Indonesia meningkat hingga 78% dari tahun sebelumnya.
Angka ini memberi sinyal bahwa ruang publik kini semakin dipengaruhi media digital.
Analisis wacana media (media discourse analysis) mengkaji bagaimana isi-berita dan konten media membangun makna, mengkonstruksi kelompok sosial, serta mempengaruhi sikap dan perilaku.
Metode populer seperti model tiga-dimensi Norman Fairclough sering diterapkan dalam penelitian terbaru media di Indonesia.
Salah satu tren utama adalah fragmentasi narasi — media digital memungkinkan munculnya banyak suara, baik arus utama maupun alternatif.
Namun, tantangannya disinformasi dan echo-chamber. UNESCO dalam dokumen Global Framework for Media and Information Literacy menyebut bahwa literasi media menjadi kunci agar publik tidak terseret arus wacana yang manipulatif.
Di Indonesia, Komdigi mendukung program literasi digital dengan “empat pilar” yaitu: cakap digital, aman digital, budaya digital, dan sejahtera digital.
Program ini diluncurkan September 2025, sebagai respons terhadap pertumbuhan cepat konsumsi media digital.
Dalam studi kontemporer, ditemukan bahasa dan metafora yang digunakan media dapat memperkuat stereotip dan bias.
Misalnya, penelitian kritis pada koran cetak di Indonesia tahun 2025 menemukan kata-kata seperti “ancaman” atau “invasi” sering digunakan dalam lapangan pemberitaan politik, meningkatkan rasa kecemasan publik.
Media juga menjadi arena perebutan narasi global dan lokal. Sebagai contoh, wacana perubahan iklim, pandemi, atau konflik kawasan sering dipresentasikan dengan frame berbeda di media tradisional dan media daring Indonesia.
Analisis menunjukkan publik di Asia Tenggara lebih percaya berita yang mengandung elemen lokal-nasional dibanding narasi internasional saja.
Implikasi penting bagi publik: saat media membentuk narasi berat sebelah, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan kritis dan literasi wacana.
Dengan demikian, mereka tak hanya jadi konsumen pasif berita, tetapi juga dapat mengidentifikasi agenda, bias, dan sumber yang kredibel.
Analisis wacana media di 2025 menunjukkan bahwa media tidak sekadar penyalur informasi, tetapi aktor penting dalam demokrasi dan kehidupan sosial.
Dengan literasi yang meningkat dan regulasi yang adaptif, publik dan pembuat kebijakan dapat bekerja sama untuk memastikan media digital tetap sehat dan produktif.
Di balik setiap wacana media, selalu ada kekuatan sosial dan ekonomi yang memengaruhi arah narasi.
Peneliti media kritis seperti Teun A. van Dijk menegaskan bahwa bahasa media sering kali digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu.
Dalam konteks Indonesia 2025, isu politik dan ekonomi masih menjadi dua bidang yang paling rentan terhadap framing bias.
Platform media besar kini menghadapi tantangan baru: kecepatan publikasi sering kali mengorbankan kedalaman analisis.
Jurnalisme kilat (fast journalism) membuat banyak redaksi berlomba mengejar klik, bukan kualitas.
Laporan The Conversation Indonesia (2025) menyoroti bahwa 62% pembaca digital hanya membaca judul tanpa menelusuri isi artikel. Sebuah fenomena yang memperkuat dangkalnya pemahaman publik terhadap isu penting.
Namun, di sisi lain, media independen dan jurnalisme warga (citizen journalism) memberikan harapan baru. Mereka menghadirkan perspektif alternatif, khususnya dalam isu lingkungan, HAM, dan pemerintahan daerah.
Studi dari Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS, 2025) mencatat bahwa kanal berita lokal justru memiliki tingkat kepercayaan publik lebih tinggi dibanding media nasional, karena kedekatan dengan realitas masyarakat.
Dalam konteks akademik, analisis wacana kini tidak hanya menyoroti isi teks, tetapi juga proses produksi dan konsumsi media.
Peneliti menggunakan pendekatan multimodal: menggabungkan teks, gambar, suara, dan data visual, untuk memahami makna yang dibangun di media sosial dan atau media online.
Pendekatan ini digunakan secara luas dalam jurnal Jurnal Komunikasi Indonesia edisi Mei 2025.
Media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok menjadi arena baru bagi pembentukan opini. Menurut data We Are Social 2025, pengguna aktif media sosial Indonesia mencapai 191 juta orang, dan lebih dari 75% di antaranya mengaku mendapat berita utama dari platform tersebut.
Di sinilah analisis wacana digital menemukan peran krusial: bagaimana algoritma dan tagar (#) membentuk persepsi publik terhadap isu sosial dan politik.
Para ahli menyarankan agar pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil berkolaborasi dalam membangun ekosistem media yang sehat.
Langkah konkret termasuk penguatan regulasi anti-hoaks, pelatihan literasi digital, serta dorongan terhadap media publik yang independen.
BMN Communication Watch (2025) menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan penyiaran dan algoritma platform.
Keseluruhan analisis ini menegaskan bahwa analisis wacana media bukan sekadar kajian akademik, tetapi kebutuhan strategis dalam menjaga demokrasi digital Indonesia.
Publik perlu terus dilatih membaca makna di balik berita. Bukan hanya “apa yang dikatakan”, tapi juga “mengapa dan siapa yang mengatakan”.
Dengan kesadaran kritis, wacana media dapat menjadi ruang dialog, bukan alat manipulasi.
Taufik Hidayat, diolah dengan bantuan AI


 Mancanegara - 30 Oct 2025
Mancanegara - 30 Oct 2025